Setelah menikah dan memiliki seorang anak, barulah saya paham dan mulai tergugah kesadaran saya tentang menjadi dewasa sekaligus orang tua. Nyatanya, menjadi orang dewasa, terutama berperan sebagai orang tua itu jelas sangat sulit. Apalagi, jika ditimbang dan ditakar antara hak dan kewajiban, keduanya tentu punya porsi dan takaran yang berbeda. Malah, rasanya lebih banyak didominasi oleh kewajiban, dibandingkan dengan hak yang amat kita harapkan.
Dewasa ini khususnya, bicara tentang hak selintas terasa sesumbar. Ibarat oase di padang pasir yang samar-samar berbayang nan menggiurkan namun sulit untuk digapai keberadaannya. Sehingga, keberadaan hak ini menjadi sebuah realita yang harus diperjuangkan, khususnya oleh diri sendiri. Karena jelas, menuntut keadilan pada orang lain tentu akan terasa lebih sulit dan rentan dengan rentetan kamuflase.
Saat ini, khususnya di jaman yang penuh dengan berbagai intrik, muslihat dan ancaman, kerap membuat saya khawatir. Iya, khawatir. Karena takut kalau-kalau sebagai ibu saya salah dalam memberikan bimbingan untuk anak-anak saya. Takut jika saya salah ketika menjadi role model bagi mereka. Ditambah lagi, hitungan usia yang kian terus bertambah. Daya dan kemampuan saya pun tentu akan makin berkurang dalam mengawasi tumbuh kembang mereka.

Sehingga, berdoa dan terus bertawakal kepada Allah adalah jurus utama sekaligus menjadi andalan bagi saya dalam menjaga anak-anak. Karena saya yakin, sebaik-baiknya pelindung adalah Allah, bukanlah makhlukNya. Dari hal itu pula, saya paham akan makna berserah kepadaNya tanpa perlu meragu.
Baca Juga: Tips Jitu Atasi Stress Bagi IRT Ala Ludy
Menjadi Dewasa dan Kentalnya Budaya Patriarki dalam Struktur Keluarga
Pelajaran menjadi dewasa ini, kurang lebih banyak saya adopsi dari buku bacaan, diskusi dengan teman dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Dari orang tua? Entah, rasanya begitu ambyar dan remuk jiwa saya manakala mengingatnya. Karena, tanpa saya sadari, pendewasaan yang saya alami ini seiring dengan hadirnya berbagai konflik yang hadir dalam ruang lingkup keluarga inti saya sejak kecil. Seakan dipaksa untuk menjadi dewasa sebelum waktunya.
Ibu saya selalu bilang, kalau anak perempuan itu justru lebih cepat dewasa mentalnya, dibandingkan anak laki-laki. Sehingga, kita sebagai keluarga harus sabar dan nrimo sembari menunggu proses kematangan berpikir mereka, para anak laki-laki ini. Jelas banget dong, ini udah budaya patriarki namanya. Karena, maksud dari makna “dewasa” ini, kita para anak perempuan dituntut untuk lebih mandiri, bisa menahan sikap untuk sabar dan mengalah, serta belajar untuk sepenuh hati melayani. Penyebabnya pun terbilang klasik, lantaran ruang lingkup perempuan masih dinilai terlalu domestik, yakni enggak jauh dari dapur, sumur, dan kasur. Nah lho, jika begini gimana anak laki-laki dalam keluarga enggak semena-mena coba???
Baca Juga: Sudahkah Kita Menjadi Ibu yang Bahagia?
Adapun, pertanyaan yang selalu berkecamuk didalam pikiran saya hingga detik ini, yakni darimana sih sumber doktrinasi ini bermula?

Lantaran bertentangan, saya memilih untuk diam dan abai. Alasannya, saya sudah lebih dulu mati rasa setelah sekian lama diabaikan perasaannya, tsaaaahhh. Meski begitu, saya tetap menaruh hormat pada ibu saya. Karena, saya sendiri juga enggak ngerti dengan pemikiran ibu yang menjadikan anak laki-laki ini untuk selalu diutamakan, dijunjung, serta dilayani. Lalu, bagaimana dengan ayah saya? Entah, apa karena memang adanya perbedaan suku atau daerah dengan ibu, untuk hal yang satu ini, Ayah enggak terlalu banyak ikut campur. Dan, sepertinya akan lebih baik baginya untuk cari aman aja, ketimbang harus perang dunia melulu setiap hari.
Oh iya, bagi saya, anak laki-laki itu mentalnya harus sekuat baja, yang bahkan dalam kondisi amat kekurangan sekalipun dia mampu survive. Khususnya, dalam mengurus kehidupan pribadinya. Apalagi nih, jika dia terlahir dari orang tua yang berada. Karena, menurut saya (lagi) laki-laki yang mau berjuang untuk dapat “berdiri sendiri” di atas kedua kakinya itu HEBAT. Dan yang paling penting nih, enggak perlu lah banyak ngeluh apalagi gombal sana-sini kalau faktanya masih dimodalin dan numpang hidup sama ortu. Malu sih!
Jika sudah begitu, mending BYE aja lah yaaa…
Ujung Tombak Sebuah Keluarga Terletak Pada Kaum Lelaki (?)
Sebelumnya, saya tegaskan ya dalam hal ini saya tidak menganut paham feminis dan sebagainya lho. Cuma mungkin, saya enggak sepaham aja dengan budaya turun-temurun ini yang menjadikan pria sebagai figur yang harus dipatuhi tanpa bantahan, dilayani segala kebutuhannya, dan maklum untuk tidak dilibatkan dalam urusan rumah tangga. Mengingat, jobdesk utama mereka ya gitu sebagai breadwinner sejati dalam sebuah keluarga. Just it.
Jadi, sepulangnya mereka kerja, yaudah pure buat istirahat aja, tanpa perlu merasa ingin tahu (apalagi dilibatkan) dengan kejadian yang terjadi selama sehari penuh di rumah. Padahal, di era globalisasi saat ini, saya dan kita semua pasti sangat yakin. Bahwa siapapun itu bisa jadi breadwinner tanpa harus memandang konteks ini dari bias gender.
Meski sadar, bahwa perempuan dalam hal ini enggak selamanya bisa jalan terus di ranah eksternal. Benar, begitu? Silahkan, jawab sendiri ya…
Dan lagi, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan peran pria ya. Hanya saja, dari sejumlah pengalaman dan konflik hidup yang hingga detik ini saya rasakan kok rasanya enggak fair ya. Padahal, berumah tangga itu sejatinya tentang bekerja sama satu sama lain dengan partner hidup, bukan cuma soal happiness aja apalagi menyangkut ena-ena. Iya, KERJA SAMA. Toh, Nabi Muhammad SAW aja udah kasih contoh ke para suami untuk rela dan siap sedia membantu segala pekerjaan rumah tangga istrinya di rumah. Please, jangan ngeyel lho ya!
‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata,
كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَة
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliaupun pergi shalat”
(HR Bukhari)
Baca Juga: Tentang Gengsi, Harga Diri dan Sandwich Generation
Saatnya untuk Memutus Rantai Patriarki dalam Keluarga
Makin kesini, sudah semestinya pula bagi kita untuk berupaya memutus mata rantai patriarki ini dalam tatanan keluarga. Ini penting lho, karena sebagai ibu tentu enggak mau kan punya anak laki-laki yang enggak mandiri, effortless dan gampang menyepelekan perempuan. Duh gusti, na’udzubillah deh, jangan sampe. Termasuk pula dalam hal ini, adil dalam memberikan kesempatan or peluang yang sama bagi anak-anak perempuan untuk mengembangkan passionnya di ranah publik. Serta, tidak ada lagi pengecualian bagi anak laki-laki untuk diberikan tugas domestik di rumah, seperti memasak dan mencuci piring misalnya.
Dimana, tujuan utamanya ialah untuk menebar manfaat seluas-luasnya. Karena, selama ini sering banget kan kita dengar judgement terkait beberapa profesi yang meragukan kapasitas perempuan dalam prosesnya. Beuhhh, kalau ada nih yang kayak begini, cemplungin juga nih ke laut, hehe.
Adapun, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai patriarki ini adalah menciptakan relasi yang setara dengan pasangan. Yakni, sebuah hubungan yang mana dia mau mendukung, siap untuk bekerja sama, menghargai, serta tidak memandang perempuan sebagai makhluk nomor dua dalam tingkat hirarki.
Karena, seringkali tanpa kita sadari perempuanlah yang kerap menjadi korban patriarki melalui stigma-stigma dan keterkaitan gender yang dikontruksikan secara umum oleh masyarakat kita sejak dulu. Merasa bahwa setelah menikah kemerdekaannya sebagai manusia utuh seolah terenggut secara paksa. Padahal, jika dari awal pasangan dapat memahami ini sebagai sebuah hak yang harus dipenuhi, jelas kondisi ini tidak akan terjadi. Sehingga, tidak lagi memandang perempuan sebagai makhluk kodrati dengan sebelah mata.
So, intinya carilah suami yang mau diajak kerja sama dalam segala hal, menghargai kesetaraan dalam berumah tangga dan tanggung jawab (bukan kaleng-kaleng), CATET! Baru, setelah itu pantas untuk disebut sebagai pemimpin keluarga yang sebenarnya. Well, kira-kira seperti apa nih pendapatmu tentang budaya patriarki dalam keluarga? Yuk, sharing! Semoga bermanfaat, SALAM WARAS!
Ludy
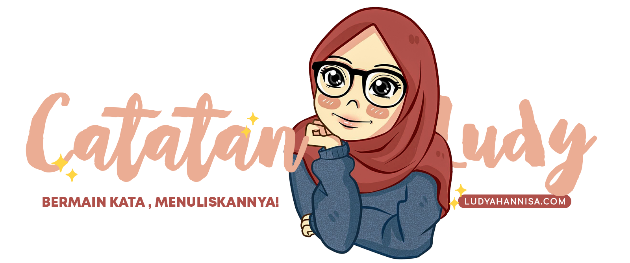



One thought on “Tentang Kerja Sama dan Budaya Patriarki dalam Keluarga”